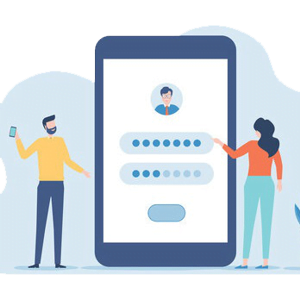Di Sa’dan, salah satu kecamatan di Toraja Utara yang dilintasi sungai besar bernama sama, para penenun baik tua maupun muda masih aktif menenun kain dengan alat tradisional seperti yang ada di Jawa dan Sumatera, atau biasa disebut gedogan atau pelantai. Ada pula yang menenun secara berkelompok di rumah tongkonan atau di bawah lumbung padi alang. Kesamaan motif tongkonan dengan kain tenun menunjukkan bahwa kedua bentuk kesenian tersebut saling menginspirasi dan mempengaruhi.
Meskipun kain ini terutama ditenun untuk kebutuhan dan upacara mereka sendiri, kain ini juga dijual sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. Perempuan adat di Sa’dan juga pernah bekerja dengan anggota industri fesyen Indonesia seperti Toraja Melo untuk memproduksi kain untuk penggunaan komersial. Menenun sebagai kegiatan spiritual sedang mengalami transformasi ekonomi. Kini, dana tersebut dapat menopang pendapatan keluarga dan dapat menutupi biaya sekolah anak-anak.
Awalnya kain tenun Toraja menggunakan benang katun yang dipintal dengan tangan dan pewarna alami yang ditanam di sekitar kebun, di ladang, dan hutan. Salah satu pewarna tersebut adalah tanaman tarum yang menghasilkan warna biru nila. Pewarna lainnya menggunakan akar mengkudu dan kunyit. Dahulu kala, Toraja juga mendapatkan pewarna hitam dari daun katakante dan lumpur yang bersumber dari ladang tempat kerbau dipelihara. Menurut salah satu warga Toraja, penggunaan lumpur yang dicampur dengan urine atau kotoran kerbau akan membantu mengunci pewarna. Kain tenun yang diwarnai melalui proses pewarnaan lumpur disebut pote, dan dipakai sebagai ikat kepala atau kerudung oleh kerabat orang yang meninggal sebagai simbol duka.
Saat ini di Sa’dan Anda bisa menemukan berbagai macam warna, teknik, dan motif pada kain tenun. Variasi kain terus berkembang seiring perubahan selera. Bagi penenun Sa’dan, kain tenun merupakan wujud kebebasan berekspresi dan mewakili estetika individu perempuan adat. Secara tradisional, tenun juga menegaskan kewenangan perempuan adat untuk mengelola rumah tongkonan dan wilayah adat di ladang atau hutan yang ditanami tanaman kapas dan pewarna alami.
Teknik dan motif kain tenun Toraja yang dibuat oleh kelompok perempuan adat di Sa’dan terdokumentasi dengan baik dalam dua publikasi Toraja Melo berjudul Untanun Katuoan: Kehidupan Sehari-hari Penenun Sa’dan Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia (2014) dan Untanun Kameloan: Wastra Toraja, Mamasa, Kalumpang, Rongkong, Sulawesi, Indonesia (2014).
Kegiatan menenun mengalami keterpurukan di Sa’dan. Arus modernisasi dan semakin banyaknya masyarakat Toraja yang pindah ke kota-kota besar berdampak pada menurunnya penggunaan dan permintaan terhadap kain tenun. Terjadi pula peralihan dari benang katun buatan tangan dan bahan pewarna alami ke benang berwarna sintetis, yang awalnya membuat kain tenun lebih mudah dan cepat diproduksi dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian peristiwa krisis keuangan tahun ’98 dan Tragedi Bom Bali menurunkan jumlah wisatawan asing yang menjadi pembeli utama kain tenun. Sejak tahun 2008 Toraja Melo telah berupaya untuk merevitalisasi industri tenun lokal melalui program yang dirancang untuk memberdayakan dan mengorganisir perempuan adat di Sa’dan.
Kini, seiring dengan pesatnya pertumbuhan pariwisata, wisatawan dalam dan luar negeri bisa kembali menikmati kain tenun hasil karya perempuan Toraja. Di Sa’dan kita tidak hanya bisa menemukan tenun ikat Rongkong dan Galumpang, tapi juga tenun polos bermotif lungsin dengan garis warna-warni, seperti Parramba’, Pamiring, Pa’bunga-bunga, Mata Papa’, dan masih banyak lagi. Ada juga Maa’ berbentuk persegi panjang dengan motif mirip Patola India, dan Sarita dengan motif panjang yang merinci figur leluhur, hewan ternak, dan pola geometris yang terlihat pada rumah tongkonan. Kedua jenis kain tersebut dibuat dengan teknik lukis tangan dan stempel kayu atau bambu (tahan celup, lukis tangan, dan celup dengan stempel bambu atau kayu).
Salah satu tokoh penting di kalangan seniman penenun Toraja adalah Nenek Panggau. Tanpa berkacamata, matanya masih dengan cekatan memintal benang katun dan tenun. Ketika ditanya berapa umurnya, dia dengan lembut menjawab, “80 tahun, tapi saya lupa tahun berapa saya dilahirkan.” Anak-anaknya setidaknya berusia setengah abad dan wajahnya penuh kerutan halus.
“Cucu pertama saya sudah mulai belajar memintal benang kapas. Tapi dia belum lancar dan masih berantakan.” Yang dia maksud adalah keterampilan memintal kapas menjadi benang. “Aku akan mati cepat atau lambat,” kata Nenek Panggau, “dan keterampilan ini akan punah!”
Apa yang dikatakannya memperkuat harapan bahwa perempuan adat Sa’dan – baik tua maupun muda – terus melestarikan praktik tenun Toraja. Namun dengan memberikan dukungan dan akses terhadap sumber daya kepada perempuan, mereka dapat mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan dan tradisi leluhur mereka.